
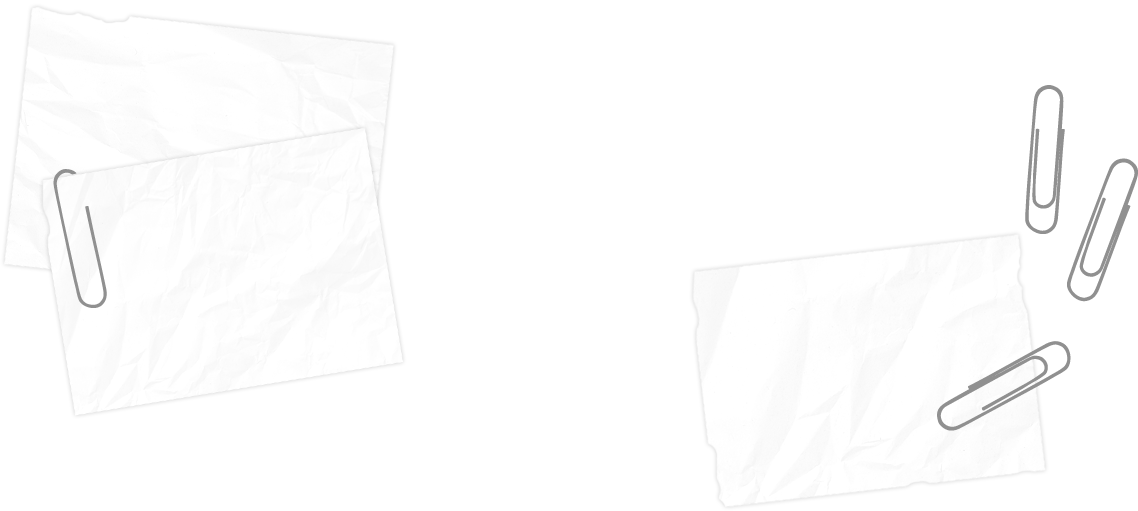
(Not) Alone in Otherland

Saya mulai merasa kehilangan diri saya sendiri. Saya sempat bertanya-tanya apa pilihan saya ini benar? (Andry)
Dan ternyata, memang sebuah sapaan sesimpel ‘halo’ dalam berbagai bahasa merupakan jurus yang sangat ampuh untuk membuka pembicaraan, dan juga jalan pertemanan dengan orang-orang dari berbagai negara. (Fei)
Jika ada yang memiliki mesin waktu dan bertanya apakah saya ingin kembali ke masa lalu, saya akan meminta kembali ke masa 100 hari di Korea ini. Bukan untuk mengubahnya, melainkan untuk menikmatinya lagi. (Lia)
Sendirian menjelajah negeri orang yang bahkan mereka tidak fasih bahasanya. Itulah yang dialami Lia, Fei, dan Andry pada awalnya.
Mereka berangkat bermodalkan nekad dan memulai petualangan sebagai siswa bahasa di Seoul, Shanghai, dan Tokyo. Penuh kekhawatiran, namun juga penuh kegembiraan dan rasa penasaran yang meluap.
Berulang kali Lia, Fei, dan Andry terus menantang diri sendiri untuk melakukan hal-hal baru. Proses yang membawa mereka berkenalan dan menemukan sahabat-sahabat baru, hingga pada akhirnya, semuanya itu membawa mereka kembali, berdamai dengan diri sendiri.
SAMPLE CHAPTER...
Hey, I'm going to the country of the rising sun!
Juni 2003, saya lulus SMA dengan nilai yang tak begitu buruk, tetapi juga tidak bisa dibilang baik. Saya ikut UMPTN dan lulus kedokteran gigi UNAIR, tetapi daftar ulang tidak saya ikuti. Saya malah mengambil jalur rekomendasi SMA saya untuk bersekolah di STTS, sebuah sekolah swasta di Surabaya yang bergerak di bidang teknik. Saya memilih jurusan informatika.
Waktu tiga tahun di SMA terasa begitu cepat. Satu per satu, teman-teman saya juga memutuskan ke mana mereka akan pergi.
"Brawijaya, kedokteran," ujar siswi yang satu.
"Petra, teknik industri," ujar siswa yang lain.
Kalau daftar universitas itu hanya sebatas universitas di Indonesia, mungkin saya tak akan merasa apa-apa. Namun, daftar itu terus berlanjut, merambah sampai ke mancanegara.
"Amerika," ujar siswi yang lain. "Aku tolak tuh beasiswa Singapura."
"Singapura," jawab siswi yang mengikuti ujian beasiswa Singapura yang sama dengan saya. Saya gagal. Dia lolos. Saya ingat rasa iri menyelimuti diri saya waktu itu, tetapi saya maklum, karena dia langganan peringkat tiga besar di sekolah.
"Australia," ujar siswa yang lain.
"Jerman."
"Taiwan."
"China."
And the country list goes on and on and on, sampai akhirnya saya tak bisa lagi menahan rasa iri saya pada mereka yang bisa bersekolah di luar negeri. Saya memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Tetapi, saya tahu keluarga tak akan menyetujui karena alasan biaya. Jadi, jalan satu-satunya bagi saya adalah menemukan sumber dana yang lain agar saya bisa pergi ke suatu tempat untuk belajar.
Singkat cerita, saya mendapatkan beasiswa itu. Akhir tahun 2003, saya mendapatkan berita itu waktu saya sedang tidur siang. Sambil sedikit terkantuk-kantuk dan separuh tertidur, saya mengangkat telepon dari kedutaan besar Jepang di Jakarta.
"Andry Setiawan?" tanya orang itu dari seberang telepon.
"Ya?" jawab saya ogah-ogahan dengan mata terpejam.
"Kamu diterima beasiswa Jepang. Beasiswa penuh dan kami akan membiayai pengeluaran sehari-harimu juga."
Hmmm...?
"Halo?" petugas itu berkata sekali lagi, terdengar bingung karena saya tidak bereaksi sama sekali.
Pertama, saya masih mengantuk dan tidak bisa mencerna informasi tadi dengan baik di telinga saya. Kedua, saya sudah hampir menyerah karena jangka waktu yang lumayan panjang untuk menunggu hasilnya. Jadi, datangnya telepon ini sama sekali tak saya duga.
"Saya ke Jepang?" tanya saya. "Betul? Tidak salah?"
Setelah orang itu mengiyakan pertanyaan saya, saya mengerjapkan mata saya beberapa kali, meloncat keluar dari kamar dan berteriak kepada kedua orangtua saya yang sedang berada di toko: "Aku ke JEPANG!!"
***
Saya bukan jenis orang yang bisa memilah-milah barang dan memisahkan antara barang yang berguna dan tak berguna. Kalau saya bisa membawa rumah saya, saya bakal membawa seluruh rumah saya ke Jepang, seperti seekor kura-kura yang selalu menggendong rumahnya.
Bukan berarti saya serakah. Saya hanya khawatir tentang berbagai hal. Kalau diingat-ingat lagi sekarang, saya merasa konyol.
Bagaimana kalau di sana saya tidak bisa menemukan sampo dan sabun? Bagaimana kalau saya tidak cocok dengan makanan di sana? Daftarnya sampai banyak sekali. Bahkan hal konyol seperti: Bagaimana kalau nanti saya tiba-tiba ingin mendengar Billy Gillman dan di sana tidak ada?
Pokoknya, saya ingin membawa semua yang saya bisa. Sialnya, orangtua saya setuju dengan saya. Alhasil, inilah barang bawaan saya ke Jepang: Tas travel hijau besar, tas koper biru berisi bahan makanan, tas bahu kecil berisi dompet dan paspor, dan tas punggung yang entah isinya apa. Saya lupa.
Konyol bukan?
Saya menyeret semua barang bawaan saya pagi-pagi buta di Bandara Soekarno-Hatta. Kedua orangtua dan kedua adik melepas saya bersama paman dan bibi.
Waktu itu saya merasa hampa. Hampa bukan berarti saya merasa kehilangan sesuatu. Juga bukan perasaan rongga hitam kelam yang seharusnya diisi dengan sepercik kebahagiaan karena mimpi saya ke luar negeri akhirnya terkabul juga. Bukan. Bukan itu. Sampai sekarang saya masih belum bisa menemukan kata yang tepat untuk menyebut perasaan saya waktu itu.
Saya ke luar negeri karena iri terhadap orang lain. Saya memilih jurusan bukan berdasarkan isi hati saya, tetapi berdasarkan realita bahwa seseorang butuh uang untuk hidup. Seolah saya tidak memiliki cita-cita apa pun. Seolah saya berada di dunia ini hanya untuk bertahan hidup.
Kehampaan seperti itulah yang saya rasakan.
Kosong. Nihil.
Saya mulai merasa kehilangan diri saya sendiri. Saya sempat bertanya-tanya apa pilihan saya ini benar? Tetapi kemudian, saya menyingkirkan pikiran itu dari otak saya dan mulai melangkahkan kaki saya sambil menyeret beban saya. Baik yang kasat mata, maupun yang tak kasat mata.